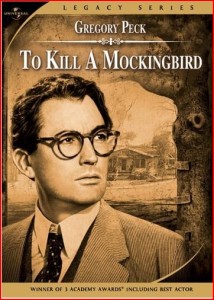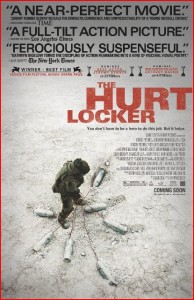Have you found joy in your life? Has your life brought joy to others? ~ Carter Chambers
Sekali lagi. Tentang kehidupan. Tentang waktu. The Bucket List (2007) mengusung ide yang sederhana yang manusia dengan kesibukan dunia materialisme hari ini sering luput memikirkan bagaimana mereka menjalani hidupnya. Sampai mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan hidup lama lagi.
Dimainkan dengan apik oleh dua aktor tua yang masih mempesona, Morgan Freeman dan Jack Nicholson, The Bucket List, bercerita tentang dua orang tua dengan dua latar belakang, karakter, dan kesukaan yang berbeda namun punya kesamaan yang sama, yaitu keduanya menderita kanker ganas dan akan menghadapi kematian dalam waktu dekat. Carter (Freeman) dan Edward (Nicholson) bertemu pertama kalinya di sebuah kamar rumah sakit. Carter adalah seorang montir mobil yang suka dengan hal-hal trivia. Dia menangkap informasi kecil yang biasanya dianggap remeh-temeh. Sedangkan Edward adalah seorang milyuner. Rumah sakit dimana mereka dirawat adalah salah satu usaha milik Edward.
Singkat cerita, mereka akhirnya bisa bersahabat. Bisa jadi, mau tidak mau harus begitu karena mereka tinggal di kamar yang sama. Edward yang baru saja dituduh tidak mengurus rumah sakitnya dengan baik, harus sekamar dengan Carter untuk memberikan citra yang baik kepada masyarakat. Carter, walaupun hidup sederhana, tapi kaya dengan cinta. Istri dan anaknya datang berkunjung beberapa kali. Sedangkan Edward yang sangat sibuk mengurus bisnisnya, hanya dikunjungi oleh asistennya yang menyipkan segala sesuatnya. Bahkan Edward menyebut, dari empat pernikahannya yang tidak tahan lama, istri yang paling setia adalah istri kelimanya, yaitu pekerjaannya.
Suatu hari ketika Carter membuat daftar hal-hal yang ingin dia lakukan sebelum dia mati, dokter memberitahukan bahwa umurnya tidak lama lagi. Kanker terus menggerogotinya, dan jika dia beruntung, dia hanya akan hidup enam bulan sampai satu tahun lagi. Beberapa saat sebelumnya, Edward sudah divonis hal yang sama. Shock dan terkejut, pastinya. Dia membuang daftar miliknya karena merasa sangat terpukul oleh vonis dokter ini. Di pagi hari, ketika asisten Edward, Thomas (dimainkan oleh Sean Hayes) datang menjenguk, dia menemukan daftar yang dibuang ke lantai. Edward yang ingin tahu, akhirnya melihat daftar itu. Bisa ditebak, daftar itu berisi hal-hal luar biasa yang mungkin tidak dilakukan orang kebanyakan. Misalnya hal-hal yang menantang seperti skydiving, sampai hal-hal yang mulia seperti melakukan sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain dengan penuh totalitas. Continue reading “Bersiap Mati: Belajar dari The Bucket List .”